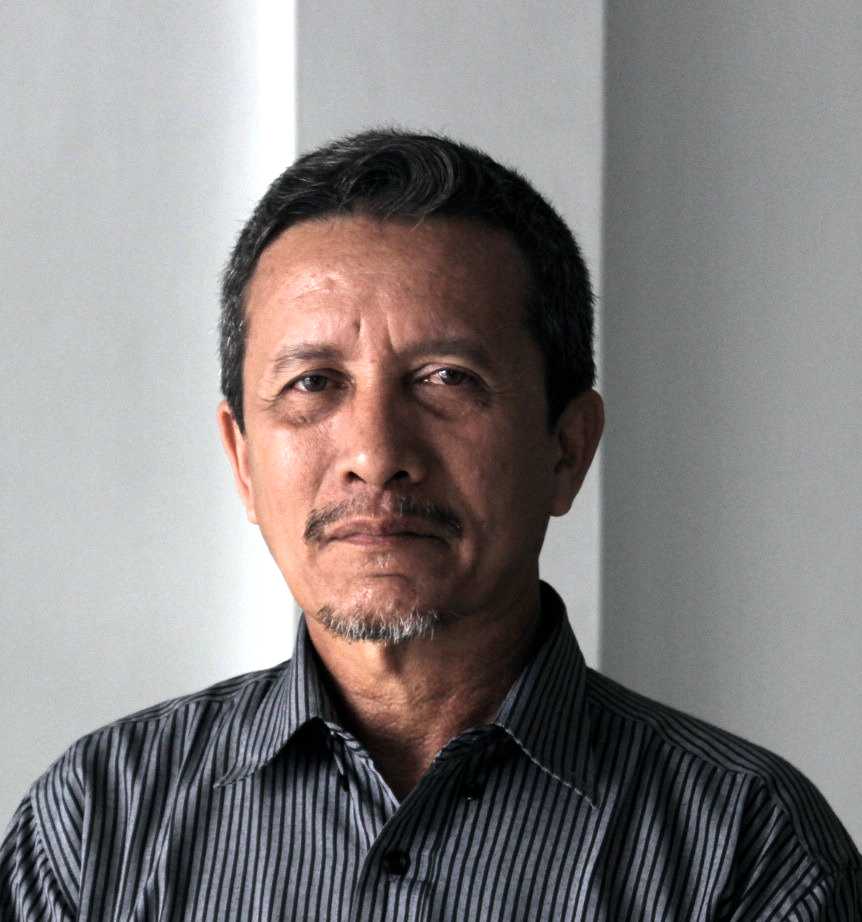
Sanusi M. Syarif / Analis MAA, Pemerhati Isu Perbatasan Gampong dan Mukim
Meuligoeaceh.com - GERBANG Lawe Pakam, tahun 1992. Suasana di kawasan perbatasan Aceh-Sumut itu begitu ramai. Mobil-mobil dinas dari dua delegasi—Aceh dan Sumatera Utara—berdatangan dari dua arah: dari Kutacane di sisi Aceh dan dari wilayah Karo di sisi Sumut. Semua kendaraan menumpuk di sisi Aceh, tepatnya di kawasan perbatasan Lawe Pakam, Kecamatan Lawe Sigala-gala.
Delegasi dua provinsi itu berkumpul untuk membahas penetapan batas wilayah administratif. Pertemuan berlangsung di salah satu sekolah di kawasan tersebut. Di dalam forum, pernyataan Bupati Karo cukup mencolok. “Kita ini bersaudara. Kesepakatan penetapan batas tidak akan mempengaruhi hak warga atas tanah dan kepemilikannya,” ujarnya.
Namun di luar forum, beredar informasi yang bertentangan. Kawasan dari Perbulan (sebelah timur Lawe Pakam) hingga Lawe Balang sesungguhnya merupakan bagian integral dari Tanah Alas. Wilayah ini telah menjadi bagian dari Aceh sejak masa sebelum Kesultanan Aceh, bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan adat yang lebih tua.
Memang, penetapan batas administratif tidak serta merta menghapus hak kepemilikan individu atas tanah. Tetapi, dampaknya sangat besar terhadap sistem tata kelola wilayah, pendapatan daerah, tanah ulayat, dan layanan publik lainnya. Sejak 1992, kawasan dari gerbang Lawe Pakam hingga Lawe Balang secara resmi masuk dalam wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Aceh kehilangan kendali administratif atas wilayah subur tersebut sepanjang kurang lebih 20 kilometer.
Pasca pemekaran administratif, kawasan tersebut diubah menjadi Kecamatan Lau Baleng. Sementara desa-desa lainnya yang berada dalam Kecamatan Mardinding, dipisahkan menjadi wilayah tersendiri: Kecamatan Mardinding Berastagi.
Bagi masyarakat Alas, Lawe Balang bukan hanya nama sungai atau tempat. Ia adalah simbol batas alamiah dan kesepakatan antara dua kerajaan: Tanah Alas dan Tanah Karo. Dalam bahasa Alas, “Lawe Balang” berarti sungai batas, dan dalam bahasa Karo dikenal sebagai “Lau Baleng” dengan arti yang sama. Sungai ini menjadi jalur penting yang menghubungkan wilayah timur Tanah Alas dan Karo.
Kesepakatan batas ini bahkan tercatat dalam dokumen kolonial Hindia Belanda. Staatblad tahun 1918 menyebut Lawe Balang sebagai batas wilayah antara Tanah Alas (Kejuruan Bambel) dengan Tanah Dairi, sekaligus sebagai pemisah administratif antara Residentie Atjeh dan Oostkust van Sumatra.
Migrasi Penduduk Batak ke Tanah Alas
Perpindahan penduduk antar wilayah adalah hal wajar, apalagi jika secara geografis berdekatan. Migrasi masyarakat Batak ke Tanah Alas terjadi secara signifikan sejak akhir abad ke-19. Studi Lister dan Rina (2019) mencatat bahwa gelombang awal migrasi terjadi saat Belanda menyerang Raja Sisingamangaraja XII di Paya Raja, Dairi, pada tahun 1883.
Pada 1904-1905, ekspedisi militer Belanda kedua ke wilayah Sidikalang memperparah eksodus. Banyak masyarakat Batak Toba mengungsi ke Tanah Alas, bagian selatan Salak, dan Hulu Singkil. Jalur migrasi melewati rute sempit dari Tanah Batak, Kutabuluh, Lau Baleng (Lawe Balang), hingga ke Salim Pipit dan Mbatu Bulan.
Saat itu, raja dan masyarakat Alas menerima para pengungsi dengan tangan terbuka. Mereka diberikan lahan untuk digarap. Solidaritas kemanusiaan menjadi alasan utama penerimaan ini, karena para migran merupakan korban kekerasan kolonial.
Selanjutnya, setelah Belanda membangun infrastruktur jalan dari Kabanjahe ke Kutacane, serta jalur ke Sidikalang, mobilitas antarwilayah makin meningkat. Sidikalang menjadi titik transit migran dari Toba Holbung, Humbang, dan Silindung menuju ke Tanah Alas dan Singkil.
Sebagian besar pekerja konstruksi jalan dan jembatan dari Batak Toba akhirnya menetap di Tanah Alas. Mereka membawa serta keluarga dan kerabat. Pemukiman mereka tumbuh di daerah seperti Titi Panjang (Kejuruan Bambel), Pulo Nas, Lawe Pertanduk, hingga Lawe Sigala-gala.
Masalah Perbatasan dan Administrasi
Meningkatnya populasi migran di kawasan perbatasan membawa dampak tersendiri. Banyak di antara mereka yang mengurus dokumen kependudukan dan pertanahan bukan di wilayah tempat tinggalnya, melainkan di kampung halaman atau daerah asal. Praktik ini berdampak pada pengelolaan layanan publik, program pembangunan, dan bahkan menimbulkan potensi konflik antarwilayah.
Sengketa batas seperti ini tidak hanya terjadi di Aceh Tenggara. Persoalan serupa muncul di sepanjang garis batas Aceh-Sumut: dari Aceh Tamiang-Langkat, Aceh Tenggara-Karo, hingga Subulussalam-Pakpak Bharat dan Singkil-Tapanuli Tengah.
Untuk menelusuri akar persoalan perbatasan ini, penting kita melihat kembali peta-peta historis. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan peta topografi lama menunjukkan batas-batas wilayah Aceh yang lebih awal sebelum terjadi peralihan wilayah.
Peta tahun 1913 dari Topografische Inrichting, Batavia, memperlihatkan batas Aceh dan Tapanuli melalui penanda alam seperti puncak gunung (Deleng). Nama-nama seperti DL Belangan Koeda, DL Pemberengen, DL Selpa, dan DL Penghulu Balang tercatat sebagai batas alamiah wilayah Aceh. Garis batas tersebut mengarah lurus ke selatan hingga mencapai pesisir dekat Pulau Mangkir Kecil (DL = Deleng, artinya gunung dalam bahasa Singkil).
Dalam peta Hindia Belanda 1932-1934, batas terakhir tercatat di DG Pantjinaren hingga pantai Oejoeng Manoekmanoek. Semua ini memperkuat bahwa wilayah daratan dan laut di sekitar Pulau Mangkir adalah bagian integral dari Tanah Singkil, Aceh.
Sumut Abaikan Kesepakatan 1992
Kesepakatan batas wilayah Aceh–Sumut pada 1992 sebenarnya tidak berdiri sendiri. Meski saat itu Aceh kehilangan Lawe Balang dan Lawe Pakam ke wilayah Karo, Pulau Mangkir dan sekitarnya tetap diakui sebagai wilayah Aceh. Namun belakangan, Sumatera Utara tampaknya mengabaikan kesepakatan tersebut.
Peta-peta topografi dan RBI menunjukkan bahwa beberapa kilometer persegi wilayah daratan Aceh kini telah dikuasai oleh Sumut. Perubahan ini bukan cuma persoalan batas administratif, tetapi juga mencakup hak historis, penguasaan tanah, dan identitas kolektif masyarakat Aceh.
Kisah peralihan wilayah dari Lawe Balang hingga Pulau Mangkir menggambarkan bagaimana batas-batas wilayah tidak hanya ditentukan oleh garis di atas peta, tetapi juga oleh sejarah, migrasi, dan kebijakan politik masa lalu. Peninjauan ulang terhadap peta lama dan dokumen kolonial adalah langkah penting untuk mengurai simpul-simpul konflik perbatasan dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan.[]









